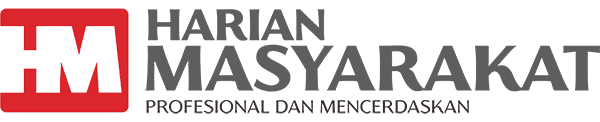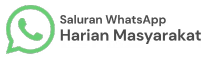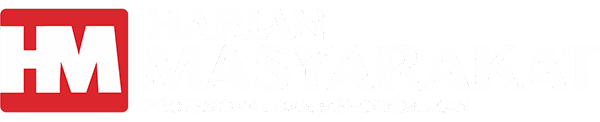Harian Masyarakat | Krisis iklim kini bukan hanya isu lingkungan. Ia sudah menjadi persoalan kesehatan mental, terutama bagi generasi muda. Dari Kanada hingga Indonesia, muncul gelombang baru kecemasan yang disebut eco-anxiety atau kecemasan ekologis, rasa takut kronis terhadap masa depan bumi yang kian memburuk.
Fenomena ini membuat banyak remaja merasa kehilangan kendali atas masa depan mereka. Mereka cemas bumi akan hancur, laut naik, hutan terbakar, dan udara makin tak layak hirup. Bagi sebagian, kekhawatiran itu berubah menjadi stres, depresi, bahkan keinginan untuk tidak punya anak karena merasa dunia tidak lagi aman.
Fakta Global: Generasi Muda Hidup dalam Ketakutan Iklim

Penelitian di Athabasca University, Kanada, menunjukkan 37 persen remaja usia 13–18 tahun merasa perubahan iklim memengaruhi kesehatan mental mereka. Mereka melaporkan gejala seperti stres, cemas, sedih, dan takut kehilangan rumah atau mata pencaharian akibat cuaca ekstrem. Sebagian bahkan takut menjadi orang tua di dunia yang makin rusak.
Peneliti Gina Martin menegaskan bahwa anak muda kini bukan hanya sadar lingkungan, tapi juga merasakannya secara emosional. Banyak dari mereka mengalami sakit kepala, lemas, dan gangguan pernapasan saat terpapar polusi atau asap kebakaran hutan. “Mereka tahu tubuh dan pikirannya sama-sama terdampak,” ujarnya.
Fenomena serupa muncul di Australia. Riset Curtin University menemukan lebih dari 80 persen mahasiswa Gen Z merasa prihatin terhadap perubahan iklim, namun hanya 35 persen yang aktif dalam gerakan lingkungan. Meski demikian, mayoritas menyalurkan kecemasannya lewat media sosial.
Dora Marinova, peneliti di universitas tersebut, menyebut keresahan itu bukan sekadar ketakutan, tapi reaksi terhadap ketidakadilan. “Mereka merasa diintimidasi oleh kurangnya tindakan nyata dari pemerintah untuk melawan perubahan iklim,” katanya.
Eco-Anxiety: Luka Psikologis yang Nyata
Menurut American Psychological Association (APA, 2017), eco-anxiety adalah ketakutan kronis terhadap kehancuran lingkungan. Ia bukan sekadar rasa khawatir biasa, tapi kecemasan mendalam yang bisa mengganggu tidur, memunculkan rasa bersalah, dan menurunkan motivasi hidup.
Fenomena ini sering berjalan bersama kondisi psikologis lain seperti solastalgia, rasa kehilangan terhadap lingkungan yang berubah atau rusak meskipun seseorang tidak berpindah tempat. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Glenn Albrecht pada 2005, menggambarkan kesedihan saat rumah sendiri tak lagi memberi kenyamanan karena rusak oleh aktivitas manusia.
Sebuah tinjauan ilmiah dari University of Zurich terhadap 19 studi global menunjukkan bahwa solastalgia memiliki hubungan kuat dengan depresi, kecemasan, dan stres pascatrauma (PTSD). Di Jerman, misalnya, masyarakat sekitar tambang terbuka memiliki tingkat stres mental hingga 0,53, lebih tinggi dibanding korban bencana sesaat seperti banjir atau kebakaran.

Ketika Alam Menjadi Sumber Trauma
Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015 menimbulkan lebih dari 500.000 kasus ISPA dan kerugian ekonomi Rp221 triliun. Namun, dampak yang jarang dibicarakan adalah trauma psikologis seperti eco-anxiety, terutama bagi anak muda yang tumbuh di tengah kabut asap.
Di Jakarta, ancaman rob dan penurunan tanah menambah ketakutan akan kehilangan rumah. Di pesisir, nelayan menghadapi badai yang makin sering, sementara petani gagal panen karena pola hujan yang tak menentu. Semua ini membentuk memori ekologis, ingatan kolektif bahwa bumi tempat mereka hidup tidak lagi aman.
Mengapa Gen Z Paling Rentan?
- Kesadaran Lingkungan yang Tinggi
Mereka tumbuh dalam banjir informasi tentang bencana dan kepunahan. Kesadaran ini membuat mereka peduli, tapi juga rentan cemas. - Paparan Media Sosial yang Berlebihan
Linimasa penuh berita krisis iklim memicu eco-fatigue atau kelelahan emosional akibat paparan berulang tanpa ruang pemrosesan. - Betrayal Anxiety
Mereka merasa dikhianati oleh generasi sebelumnya dan pemerintah yang dianggap gagal bertindak. Riset Hickman et al. (2021) menunjukkan 83 persen anak muda merasa orang dewasa telah gagal menjaga bumi. - Masa Perkembangan Psikologis yang Rawan
Fase remaja adalah masa pencarian identitas. Ketidakpastian masa depan membuat mereka mengalami kecemasan eksistensial. - Minimnya Saluran Aksi yang Bermakna
Ketika ingin berbuat, banyak yang merasa upayanya kecil dan sia-sia. Kondisi ini memicu eco-paralysis, perasaan lumpuh dan tidak berdaya menghadapi masalah lingkungan.
Eco-Aniety Adalah Tanda Peduli, Bukan Kelemahan

Psikolog lingkungan seperti Susan Clayton (2020) menyebut eco-anxiety bisa bersifat adaptif. Artinya, eco-anxiety adalah tanda empati ekologis dan kepekaan moral terhadap planet yang terluka. Tantangannya adalah mengubah emosi itu menjadi energi sosial yang konstruktif.
Penelitian Ojala (2012) membuktikan bahwa strategi problem-focused coping, berfokus pada solusi nyata, lebih efektif menurunkan eco-anxiety dibanding menghindari isu lingkungan.
Mengubah Eco-Anxiety Menjadi Aksi
- Mulai dari Tindakan Kecil
Menanam pohon, mengurangi plastik, membuat kompos, atau jadi relawan. Tindakan kecil memberi rasa kendali dan meningkatkan kepercayaan diri bahwa Anda bisa berkontribusi. - Bangun Literasi Emosi dan Ruang Aman
Validasi perasaan cemas melalui aktivitas seperti meditasi alam, menulis jurnal lingkungan, atau bergabung dalam komunitas “climate café” tempat orang bisa berbagi keresahan tanpa dihakimi. - Perkuat Dukungan Institusional
Sekolah, kampus, dan pemerintah perlu menyediakan layanan konseling khusus dan melibatkan anak muda dalam kebijakan lingkungan. Suara mereka harus didengar dalam perencanaan aksi iklim. - Bangun Narasi Harapan
Media dan influencer harus menampilkan cerita positif: petani yang berhasil beradaptasi, inovasi energi bersih, atau komunitas muda yang menanam hutan kembali. Riset Nabi et al. (2022) menunjukkan framing positif meningkatkan niat pro-lingkungan tanpa menimbulkan putus asa. - Kembangkan Identitas Ekologis
Jadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari identitas, bukan beban. Pilih gaya hidup berkelanjutan sesuai kemampuan: konsumsi lokal, investasi hijau, atau mode etis.

Dari Duka ke Harapan
Eco-anxiety adalah cermin dari kesadaran baru umat manusia. Ia menunjukkan bahwa generasi muda masih memiliki empati dan keinginan memperbaiki dunia. Yang berbahaya bukan kecemasannya, tapi ketika kecemasan itu diabaikan dan berubah menjadi apatisme.
Indonesia butuh generasi yang bukan hanya sadar, tapi juga tangguh. Generasi yang mampu memproses duka ekologis dan eco-anxiety menjadi komitmen untuk bertindak. Karena bumi yang kita injak hari ini bukan milik kita sepenuhnya. Ia hanya titipan dari masa depan, dan tugas kita adalah mengembalikannya dalam keadaan lebih baik daripada saat kita menerimanya.