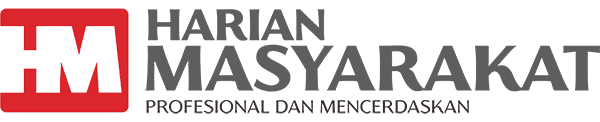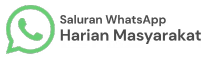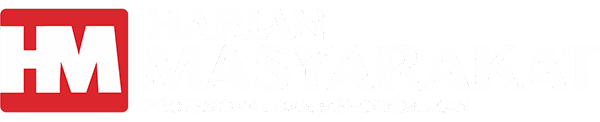Harian Masyarakat | Hari ini, 17 Agustus 2025, Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80. Delapan dekade telah berlalu sejak Sukarno membacakan teks Proklamasi di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pada 17 Agustus 1945. Pekik “Merdeka!” kala itu bukan sekadar teriakan, melainkan taruhan hidup dan janji besar untuk menanggung nasib sendiri.
Namun, delapan puluh tahun kemudian, makna kemerdekaan sering kali terasa seperti slogan yang hanya dibersihkan setahun sekali demi kepentingan seremoni. Upacara, lomba, dan karnaval rakyat memang semarak, tetapi setelah bendera diturunkan, jalan berlubang kembali diabaikan, hukum kembali tumpul, dan rakyat tetap antre panjang menunggu subsidi.

Di era digital yang penuh informasi, ujian kemerdekaan bergeser. Ia tidak lagi melawan kolonialisme fisik, melainkan kolonialisasi kesadaran. Algoritma, media sosial, dan kepentingan oligarki menciptakan ilusi kebebasan, padahal substansinya makin tergerus.
Nasionalisme yang Merosot Menjadi Ritual
Setiap Agustus, bendera merah putih berkibar di mana-mana, pidato kenegaraan disiarkan, jargon cinta Tanah Air diulang-ulang. Tetapi, apa yang sebenarnya dirayakan?
Nasionalisme Indonesia kini lebih sering hadir sebagai moralitas upacara ketimbang gagasan hidup. Lagu wajib dinyanyikan dengan khidmat, batik dikenakan di hari tertentu, dan lambang Garuda dipasang di media sosial. Namun substansi republikan; keadilan sosial, partisipasi rakyat, dan deliberasi publik, justru kian terpinggirkan.
Lebih ironis lagi, republik yang lahir dari revolusi justru sering takut pada rakyatnya sendiri. Demonstrasi mahasiswa dituduh makar, petani yang menolak tambang dicap anti-pembangunan, kritik dilabeli ujaran kebencian. Rakyat diagungkan dalam retorika, tetapi disingkirkan dari pengambilan keputusan.
Fenomena bendera One Piece yang dianggap ancaman subversif mencerminkan betapa nasionalisme resmi Indonesia kehilangan daya hidup. Nilai persaudaraan, solidaritas lintas kelas, dan perlawanan terhadap tirani justru lebih banyak ditemukan dalam simbol alternatif ketimbang dalam pidato pejabat.
Pertanyaan pun muncul: apakah 17 Agustus kini perayaan kedaulatan rakyat, atau sekadar drama simbolik untuk menutupi ketimpangan dan kegagalan elite?
Seperti pernah diingatkan Bung Hatta, “Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju masyarakat adil dan makmur.” Sayangnya, jembatan itu kerap macet di tengah jalan.
Dari Mercusuar Dunia ke Ketertinggalan Regional

Pada awal kemerdekaan, Indonesia berdiri sebagai mercusuar revolusi dunia. Sejarawan Benedict Anderson menyebut periode 1945–1949 sebagai laboratorium dekolonisasi paling penting abad ke-20. Revolusi Indonesia menginspirasi Vietnam, Aljazair, hingga Afrika. Konferensi Bandung 1955 dan Gerakan Non-Blok 1961 menjadikan Indonesia pemain utama di panggung global.
Namun hari ini, posisi itu memudar. Setelah 30 tahun Reformasi, demokrasi tumbuh, kebebasan berbicara lebih luas, tetapi kemajuan substansial masih tertinggal.
- Ekonomi: Pertumbuhan hanya sekitar 5 persen, kalah dari Vietnam yang stabil di 6–7 persen. Indonesia masih bergantung pada batu bara dan sawit, sementara tetangga beralih ke teknologi tinggi.
- Infrastruktur: Pembangunan jalan tol gencar, tetapi 38 persen jalan nasional rusak. Bandara dan pelabuhan tertinggal dibanding Malaysia dan Singapura. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih tampak sebagai simbol politik daripada strategi pembangunan terukur.
- Korupsi: Indeks Persepsi Korupsi 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 115 dunia. Korupsi tidak lagi terpusat di pusat kekuasaan, tetapi menyebar hingga ke desa dan dana bansos.
- Keadilan sosial: Rasio gini meningkat dari 0,31 (1998) menjadi 0,38 (2024). Jakarta penuh mal mewah, sementara sebagian anak di Nusa Tenggara Timur masih melawan stunting.
- Pendidikan dan hukum: Peringkat PISA Indonesia jeblok, masuk enam terbawah dunia. Indeks Negara Hukum stagnan, dan putusan pengadilan sering dipengaruhi politik transaksional.
Indonesia, yang dulu pionir Asia-Afrika, kini justru tertinggal dalam kompetisi regional.
Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, pernah menegaskan, “Perjuangan kita bukan untuk memerdekakan tanah air saja, tetapi juga untuk memerdekakan rakyat dari kebodohan dan kemiskinan.” Pesan itu semakin relevan di tengah realitas ketertinggalan kita.
Krisis Kepemimpinan dan Budaya Politik
Masalah terbesar Indonesia bukan hanya ekonomi atau infrastruktur, tetapi kualitas kepemimpinan. Politik transaksional membuat pemimpin lebih sibuk mencari dukungan jangka pendek daripada merancang visi panjang.
Sementara negara lain menyiapkan strategi abad ke-21 dengan serius, elite Indonesia terjebak pada retorika simbolis, pencitraan, dan perebutan kuasa. Korupsi menjadi habitus, hukum jadi alat tawar, dan rakyat hanya figuran dalam drama politik.
Pemimpin transformatif yang berani membongkar sistem busuk, membangun institusi bersih, dan menyiapkan generasi baru justru jarang lahir dari sistem politik yang ada. Demokrasi prosedural menghasilkan banyak aktor medioker, sementara pemimpin visioner terpinggirkan.
Pramoedya Ananta Toer pernah mengingatkan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai dirinya sendiri.” Sayangnya, penghargaan itu sering dikorbankan demi kepentingan sesaat elite politik.
Restorasi Makna Kemerdekaan

Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan proses panjang menjaga martabat bangsa. Restorasi makna kemerdekaan menuntut tiga hal mendasar:
- Pendidikan kritis dan manusia merdeka. Sistem pendidikan harus membebaskan dari sekadar orientasi pragmatisme. Generasi baru perlu ditempa sebagai manusia merdeka dengan pikiran tajam, nurani bersih, dan kesadaran sejarah.
- Kepemimpinan beretika dan visioner. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bukan hanya jujur, tetapi juga mampu mengubah integritas menjadi kebijakan konkret. Etika harus menjadi kompas, nalar menjadi penerang, dan tata kelola yang rapi menjadi alat implementasi.
- Pembangunan berorientasi peradaban. Jalan tol dan gedung tinggi harus menjawab pertanyaan: manusia seperti apa yang ingin kita lahirkan? Indonesia ditakdirkan bukan sekadar negara kepulauan, tetapi civilizational state yang menyeimbangkan teknologi dengan kearifan.
Seperti kata Hannah Arendt, kebebasan bukan hadiah yang kita terima, melainkan ruang yang harus terus dipelihara. Restorasi ini bukan nostalgia, melainkan proyek kolektif yang menuntut keberanian rakyat untuk merebut kembali naskah sejarah dari tangan elite.
Merdeka yang Hidup, Bukan Fosil
Delapan puluh tahun lalu, para pendiri bangsa mempertaruhkan hidup demi kata “merdeka”. Delapan puluh tahun kemudian, tugas kita adalah memastikan kata itu tidak berubah menjadi fosil politik.
Kemerdekaan harus dikembalikan pada substansi: martabat manusia, keadilan sosial, dan keberanian melawan ketidakadilan. Bila gagal, 17 Agustus hanya akan menjadi ritual kosong. Bila berhasil, sejarah akan mencatat bahwa di titik ini bangsa Indonesia menemukan kembali dirinya: sebagai pencipta kemerdekaan yang terus hidup, bukan sekadar pewaris simbol yang rapuh.
Merdeka bukan sekadar upacara. Kemerdekaan adalah kerja panjang menjaga akal sehat, nurani, dan keberanian. Dan di ulang tahun ke-80 ini, pertanyaan terbesarnya adalah: apakah kita siap menulis ulang lakon bangsa dengan tangan kita sendiri?
Seperti kata Sukarno, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”